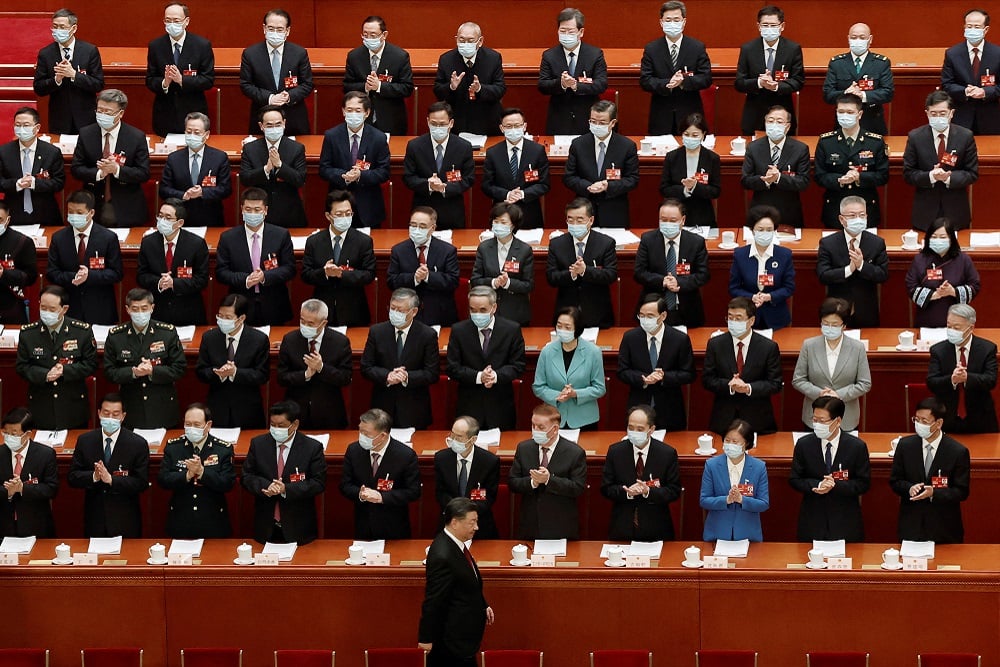Bisnis.com, JAKARTA -- Tensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China kian panas. Kedua raksasa ekonomi dunia itu saling serang menggunakan instrumen tarif. Ketegangan antara AS vs China itu mengulang peristiwa Perang Dagang Jilid 1, namun dengan tingkat eskalasi yang berbeda.
Babak baru perang dagang Jilid II antara China Vs AS, dimulai ketika Presiden Donald Trump mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff kepada China dan sejumlah negara lainnya. China kena tarif 34%. Kebijakan itu memicu ketegangan. Banyak negara protes. Beijing geram. Mereka menyiapkan aksi balasan. Semua produk AS dikenakan tarif 34%.
Aksi balasan China rupanya, memicu kemarahan Presiden Donald Trump. Politikus Partai Republik itu kemudian menambah pengenaan tarif kepada China sebesar 104%. China yang tidak mau tinggal diam merespons-nya dengan pengenaan tarif sebesar 84% kepada produk AS. Kabar terbaru, Trump kembali meningkatkan tarif kepada China menjadi 125%. Menariknya, Trump justru menunda pengenaan tarif untuk negara non-China sampai 90 hari ke depan.
"Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China kepada Pasar Dunia, dengan ini saya menaikkan tarif yang dibebankan kepada China menjadi 125%, berlaku segera," ujar Trump, Rabu kemarin.

AS dan China adalah dua negara dengan produk domestik bruto (PDB) nominal terbesar di dunia. Mereka bersaing menguasai perekonomian global. Jaringan bisnis mereka ada di mana-mana. Di Asia, Afrika, Amerika, hingga Uni Eropa. AS bisa dibilang sebagai penguasa tradisional. Apalagi, sejak berakhirnya Perang Dingin, yang secara dramatis digambarkan oleh Francis Fukuyama sebagai The End of History and The Last Man alias kemenangan liberalisme Barat.
Baca Juga
Selama beberapa dekade selanjutnya, AS dan sekutunya menancapkan hegemoninya. Mereka membentuk pakta-pakta pertahanan, termasuk pakta ekonomi di berbagai kawasan, menandai pengaruh AS dalam geopolitik global. Sampai akhirnya China, yang telah mereformasi ekonominya sejak era Deng Xiaoping, mulai tampil sebagai kekuatan ekonomi global dengan barang made in China-nya.
Peneliti China, Kerry Brown dalam artikel berjudul 'Deng Xiaoping Southern Tour' menulis bahwa Deng Xiaoping terinspirasi untuk mereformasi total ekonomi China, setelah berkeliling ke bagian selatan negaranya saat ekonomi China lesu sekitar tahun 1980-an.
Hasilnya, China mengalami lompatan yang besar. Mereka mulai membuka tirai besi. Terjadi liberalisasi perekonomian dan upaya masuk dalam pasar bebas. Shenzhen termasuk wilayah yang menjadi sasaran Deng melakukan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi ala Deng Xiaoping, telah mengubah kampung nelayan Shenzhen menjadi kota global dengan segala kemajuan teknologinya.
Proses liberalisasi ekonomi tersebut kemudian menjadikan China menjadi kekuatan perdagangan global. Sejumlah inisiasi dan investasi jangka panjangnya berhasil menopang status China sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia. One belt one road (OBOR) atau yang dikenal sebagai jalur sutra baru, tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menguatkan pengaruh China dalam lanskap geopolitik global.
Besarnya pengaruh China terekam dalam data-data yang dipublikasikan oleh lembaga global. Data Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat bahwa PDB nominal China berada di angka US$19,53 triliun. Angka ini memang masih jauh berada di bawah AS yang tercatat sebesar US$30,34 triliun. Namun pada tahun 2020 lalu, ada proyeksi bahwa ekonomi China akan melampaui AS di kisaran tahun 2028, meskipun belakangan proyeksi ini banyak direvisi karena sejumlah aspek.
Tabel Defisit Perdagangan AS-China 2020-2024
| Tahun | Ekspor | Impor | Defisit |
| 2020 | 124,5 | 432,5 | 307,9 |
| 2021 | 151,4 | 504,2 | 352,8 |
| 2022 | 154,1 | 536,2 | 382,1 |
| 2023 | 147,7 | 426,8 | 279,1 |
| 2024 | 143,5 | 438,9 | 295,4 |
Sumber: Cencus.gov, dalam miliar US$ (dolar)
Kendati demikian, dari sisi perdagangan, barang-barang made in China telah menggeser produk AS. Produk elektronik, manufaktur padat karya, teknologi kendaraan listrik, hingga artificial intelligence berkembang cukup pesat dan mulai menguasai pasar. Ekspor China adalah yang terbesar di dunia.
Pada tahun 2024, misalnya, data Customs China menunjukkan bahwa, volume perdagangan China mencapai US$6,16 triliun. Ekspor mencapai US$3,57 triliun dan impor sebesar US$2,58 triliun. Neraca perdagangan China surplus sebesar US$992,1 miliar.
Kinerja perdagangan China jelas telah melampaui AS. Data dari Cencus.gov, total volume perdagangan AS pada tahun 2024 hanya mencapai US$5,3 triliun. Angka ini terdiri dari ekspor sebesar US$2 triliun dan impor sebesar US$3,26 triliun. Berbeda dengan China, neraca perdagangan AS defisit di angka US$1,2 triliun. China adalah salah satu pernyumbang terbesar defisit neraca perdagangan AS yang tercatat pada 2024 lalu sebesar US$295,4 miliar.
Dengan besarnya volume perdagangan tersebut, ketegangan AS dan China memicu kekhawatiran banyak pihak tentang pelambatan ekonomi dan kemungkinan terganggunya rantai pasok atau supply chain global.
Sekadar catatan, sebelum Trump resmi mengobarkan perang tarif, OECD telah mewanti-wanti bahwa kebijakan tarif hanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global dari 3,2% pada 2024 menjadi 3,1% pada 2025 dan 3,0% pada 2026. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 3,3% untuk 2025 dan 2026.
Sementara itu di level regional, Asian Development Bank (ADB) juga telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik ke level 4,9%, dari 5% tahun lalu. Ekonomi China akan tumbuh melambat sebesar 4,7% tahun ini dan 4,3% tahun depan, dibandingkan dengan 5% tahun lalu. India perekonomian terbesar di Asia Selatan diproyeksikan akan tumbuh 6,7% tahun ini dan 6,8% tahun depan. Perekonomian di Asia Tenggara diperkirakan akan tumbuh 4,7% tahun ini dan tahun depan.
Namun demikan, Trump tidak peduli dengan pertimbangan atau proyeksi statisik itu. Trump tetap merasa AS diperlakukan tidak adil, sehingga menaikan tarif adalah solusinya. Kebijakan Trump ini memicu polemik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan secara satire menyebut bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Trump itu tidak ada landasan secara ekonomi.
Selain itu, banyak pihak curiga bahwa sikap keras Trump melalui tarif, sejatinya bermakna politis dan hanya ingin memaksa China ke meja perundingan. Apalagi, sebagaimana dilaporkan Blomberg belum lama ini, Trump mengatakan sedang menunggu panggilan dari pejabat China, sembari menuduh bahwa Negeri Panda salah menangani situasi.
"China juga ingin membuat kesepakatan, sangat ingin, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Kami menunggu panggilan mereka. Itu akan terjadi!" kata Trump.
Sementara itu, China sejauh ini masih berkukuh untuk melawan berbagai upaya yang mereka sebut sebagai ‘intimidasi’ ekonomi oleh Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian pernyataan resminya mengemukakan bahwa China tidak akan pernah menerima tindakan hegemonik dan intimidatif dari AS.
Lin juga menuturkan bahwa jika AS ingin menyelesaikan masalah melalui dialog, mereka harus memperlakukan orang lain dengan kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan. Namun demikian, jika AS bertindak untuk kepentingan AS sendiri, maka China tidak akan pernah menerima sikap tersebut. “China dan seluruh dunia bertekad untuk melawan tarif dan perang dagang. Respons China akan terus berlanjut sampai akhir,” tegas Lin.