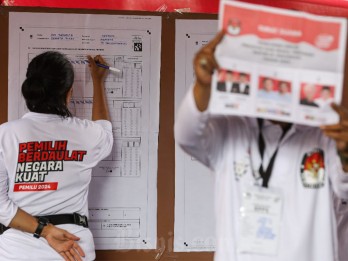Bisnis.com, JAKARTA — Gerakan 30 September 1965 yang mengakibatkan gugurnya tujuh Pahlawan Revolusi atau lebih dikenal dengan G30S PKI adalah kali ketiga pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia.
Pemberontakan PKI di Indonesia sepanjang hampir 1 abad selalu merugikan Indonesia, terutama pada 1948 dan 1965 yang memicu sejumlah pembunuhan atas sejumlah tokoh di sejumlah daerah.
Adapun, pemberontakan PKI pertama pada 1926—1927 di Banten maupun Sumatra Barat melawan Kolonial Belanda, yang sebelum 1923 bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), juga merugikan karena berakibat pada dibekukannya dan penghancuran gerakan-gerakan kebangsaan melawan penjajah.
Sementara itu, pemberontakan PKI pada 1965 mengakibatkan gugurnya tujuh Pahlawan Revolusi di Jakarta serta memicu peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru.
Tujuh Pahlawan Revolusi yang menjadi korban dalam tragedi G30S PKI di Jakarta dan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa adalah:
- Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani
- Letnan Jenderal TNI (Anumerta) Suwondo Parman
- Mayor Jenderal TNI (Anumerta) Donald Isaac Pandjaitan
- Letnan Jenderal TNI (Anumerta) Mas Tirtodarmo Haryono
- Letnan Jenderal TNI (Anumerta) R. Suprapto
- Mayor Jenderal TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo
- Kapten Czi. (Anumerta) Pierre Tendean
Adapun, pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 disertai dengan aksi-aksi pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak disukai oleh kaum komunis, termasuk Residen Sudiro, pegawai pamong praja, yang merupakan anggota Barisan Banteng dan anggota PNI, yang tentu menjadi incaran kaum komunis atau para pengikutnya.
Pada akhir Maret 1947, Pemerintah Pusat menetapkan Raden Sudiro Hardjodisastro, yang merupakan eyang dari aktor Taura Danang Sudiro atau lebih dikenal dengan Tora Sudiro, sebagai Pejabat Residen Surakarta. Kelak, Sudiro menjadi Walikota Jakarta pada 1955 dan kemudian Kepala Daerah Jakarta Raya (setingkat gubernur DKI Jakarta) periode 1953—1960.
Ketika itu kaum revolusioner PKI sedang agresif untuk menghancurkan rival-rival politiknya, termasuk Barisan Banteng.
Madiun, yang akhirnya menjadi pusat pemberontakan PKI pada 1948, hanya berjarak sekitar 100 km dari Solo sehingga wilayah di bawah kepemimpinan Sudiro pun ikut bergolak dan disertai dengan aksi culik menculik dan pembunuhan.
| Baca Juga : Raden Sudiro, Soeharto, dan Tol Jagorawi |
|---|
Hal ini juga menimpa pimpinan umum Barisan Banteng Dr Muwardi (namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit di Jebres, Solo). Muwardi, seorang dokter THT, ketika sedang melakukan operasi di rumah sakit di Jebres dijemput oleh sejumlah orang.
Sejak dia keluar dari halaman rumah sakit itu hingga kini tak diketahui dibawa kemana dan bagaimana nasibnya selanjutnya. Sama seperti halnya yang dialami oleh para pahlawan revolusi, diculik dan kemudian dibunuh.
Sudiro Akrab dengan Media Merdeka dan Pacific
Pada masa itu, sekitar tiga tahun setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, di Solo ada dua Harian yang berani menelanjangi praktik-praktik kaum komunis dan menjunjung tinggi Pancasila, yaitu Pacific yang dipimpin Imam Soetardjo dan Merdeka edisi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Dalbassa Pulungan.
Sejalan dengan keadaan zaman waktu itu, baik Pacific maupun Merdeka dicetak di atas kertas merang, kadang-kadang hurufnya mblobor tidak begitu jelas dibaca. Gambar-gambarnya pun kabur, namun isinya tetap dapat diikuti dan masih dapat dinikmati.
Merdeka dicetak di percetakan Coyudan, dengan aksara handze kadang-kadang ditata di dekat sumur, karena listrik kadang-kadang nyala, tempo-tempo mati, maka terpaksa pula dilakukan dengan menggunakan lampu teplok.
Jumlah karyawan dan wartawannya lebih kurang 30 orang, beserta keluarga masing-masing. Ketua Redaksi ada di tangan Dalbassa Pulungan, mendapat bantuan penuh dari Hetami, Darmo sugondo, Sudarso dan lain-lain.
Soebagijo I.N. dalam bukunya, Sudiro: Pejuang Tanpa Henti (Gunung Agung, 1981), menuturkan bagaimana Sudiro menjadi akrab dengan orang-orang Pacific dan Merdeka ini.
Sewaktu ada pengumuman resmi dari Pemerintah RI di Yogyakarta mengenai pecahnya pemberontakan kaum komunis yang tergabung dalam PKI di Madiun pada 18 September 1948, yang menyilakan rakyat memilih Muso-Amir yang akan membawa rakyat dan negara ke jurang kerusakan serta kebinasaan atau memilih Sukarno-Hatta yang Insya Allah akan membawa negara dan rakyat ke tempat cita-cita, Sudiro sendirilah yang membawa copy-nya ke percetakan Merdeka agar segera dapat dicetak dan disebarluaskan kepada rakyat.
Sudiro Dicegat hendak Dibunuh PKI
Ketika itu, gerombolan PKI bersiap mencegat Sudiro di dekat jembatan Mangkunegaran. Sebab, lazimnya tiap kali dia pulang dari kantor, senantiasa melewati jalan itu.
Tetapi, entah apa sebabnya pada hari itu Residen Sudiro justru ada sesuatu keperluan di lain tempat, dan sewaktu hendak pulang ke rumah dia memilih jalan lain. Gerombolan penculik terpaksa mengurungkan niatnya.
Tigapuluh tahun kemudian, setelah terjadinya peristiwa pemberontakan komunis 1948, setelah gerakan PKI 1965 dan era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Sudiro baru tahu, dari salah seorang calon penculik, bahwa gerombolan komunis hendak menculiknya.
Nasib berbeda dialami oleh Munadji, seorang pegawai Pengadilan Negeri di Ngawi. Dia adalah tamatan AMS jurusan Sastra Timur, kemudian meneruskan pelajaran ke OSVIA Sekolah Pamong praja. Waktu itu dia harus mengikuti sesuatu latihan yang diadakan Pemerintah di Solo. Selesai upacara penutupan latihan dia singgah sebentar di rumah Sudiro, karena Bu Diro masih ada kaitan keluarga dengannya.
Sewaktu dia hendak minta diri, sebenarnya Bu Diro sudah nggon- dheli, dan menganjurkan untuk bermalam saja di situ. Tetapi, Munadji menjawab: "Sudah rindu anak-anak....," maka diapun berangkatlah pulang ke Ngawi. Dua hari kemudian, diapun ditangkap oleh kaum komunis yang sudah menguasai kota tersebut.
Sewaktu gerombolan komunis bertanya kepadanya: pilih Muso-Amir atau Sukarno-Hatta, Munadji tanpa ragu menjawab: Sukarno-Hatta. Munadji dibawa ke alun-alun Ngawi dan di situ dikeroyok oleh sejumlah orang komunis sampai tidak berdaya lagi.
Munadji meninggalkan delapan orang anak, salah satu diantaranya adalah Sri Edi Swasono yang kemudian menjadi menantu Bung Hatta, sang proklamator.