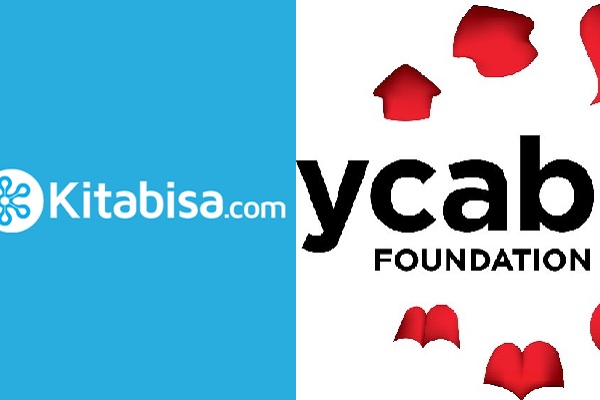Simone Bernstein dan adik laki-lakinya Jake Bernstein mulai membangun usahanya ketika berumur 17 dan 15 tahun pada 2009. Berdua menghabiskan musim panas dengan membuat website yang berisi daftar peluang bagi sukarelawan di kota asal mereka di St. Louis, Missouri, AS.
Alasannya, mereka frustrasi karena tidak adanya pusat informasi seputar peluang untuk dikerjakan para relawan. Keduannya meluncurkan situs volunTEENnation.org dan membuat sekitar 7.500 anak muda menemukan peluang menjadi sukarelawan.
Sementara itu, Sejal Hathi mendirikan lembaga nonprofit Girls Helping Girls di usia 15 tahun, dan membuat usaha sosial Girltank saat berumur 19. Girltank didedikasikan untuk memberdayakan perempuan muda secara sosial dan ekonomi dan telah menjangkau 104 negara. Lulusan Yale University bidang biologi molekular ini lahir pada 1991.
Di Indonesia ada M. Alfatih Timur yang mendirikan program urun dana (crowdfunding) KitaBisa di usia 22 tahun. Crowdfunding adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui Internet.
Ada juga Veronica Colondam, pendiri dan CEO Yayasan YCAB, organisasi nirlaba yang bertujuan mempromosikan program pengembangan pemuda melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Pada usia 29, dia meraih Vienna Civil Society Award (2001) termuda.
Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) terus berkembang menjadi program percontohan perusahaan sosial global di lima negara lainnya yaitu di Myanmar, Afghanistan, Pakistan, Uganda, Mongolia dan Laos.
Baca Juga
Ini hanya contoh, betapa mudanya mereka ketika memulai usaha sosial atau social enterprise—bentuk organisasi yang tumbuh subur dalam dekade terakhir. Kehadiran tradisi startup di dunia teknologi makin memudahkan terbentuknya wirausaha sosial.
Meski begitu, secara substansi aktivitas kewirausahaan sosial telah dimulai pada abad ke-19 ketika Vinoba Bhave mendirikan Land Gift Movement di India, Robert Owen mendirikan gerakan koperasi, dan Florence Nightingale membangun sekolah perawat pertama dan mengembangkan praktik keperawatan modern.
Kewirausahaan sosial terbukti membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, penyakit dan kematian, serta kualitas hidup yang buruk yang disebabkan ketidakmampuan manusia.
Konsep ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang banyak masalah, tapi gagal ditangani pemerintah dan dikesampingkan sektor swasta. Salah satu indikatornya tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Gini Ratio) yang termasuk tinggi, yakni 0,391.
Padahal, tingkat kedermawanan orang Indonesia termasuk tinggi berdasarkan World Giving Index (WGI) yakni di posisi dua dunia pada 2017 di bawah Myanmar. Parameter terbesar yang dicapai Indonesia adalah jumlah dana yang didonasikan dan waktu sebagai relawan, sedangkan terendah adalah kerelaan membantu orang asing.
Wirausahawan sosial di Indonesia dilakukan lewat berbagai kegiatan kreatif dan inovatif untuk menghasilkan dana guna mewujudkan misinya. Mereka mencoba menjadi unik dan berbeda, sehingga dapat menarik lebih banyak dukungan dan memperluas cakupan.
Sejalan dengan tren kemunculan startup, pengembangan kewirausaahn sosial di Tanah Air tampaknya bisa lebih cepat. Konsep lean startup yang dibawa Eric Ries mewabah dan diterapkan di luar usaha bidang teknologi.
Anda bisa memeriksa di sekolah-sekolah bisnis di Indonesia dan akan menemukan banyak ide-ide sociopreneur sedang bersemi. Kisah-kisah seperti Blake Mycoskie yang mendirikan perusahaan berorientasi profit, TOMS, tapi sekaligus memberi sepatu gratis untuk anak-anak di negara berkembang, ikut memicu gairah.
Uniknya, sebagian besar pelaku social enterprise yang penulis temukan adalah anak-anak muda dengan idealisme di kepala. Sebagian muncul dari pengalaman hidup pribadi, yang lain menuai sentuhan sistem pendidikan entrepreneurship.
Sebenarnya tidak mengherankan karena tingginya populasi penduduk usia muda di Tanah Air, yakni dengan rata-rata usia 30. Merekalah harapan Indonesia.